Allah Tidak Pernah Lepas dari Kita (Hikam 41)
Hikam nomor 41 tentang Allah yang tak pernah luput mengawasi kita sebagai manusia ciptaan-Nya.
لعجب كل العجب ممن يهرب ممن لاانفكاك له عنه ويطلب ما لابقاء له معه ((فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور. الحج: 46))
Sungguh mengherankan orang yang berlari dari dzat yang tidak pernah lepas darinya, lalu malah mencari sesuatu yang tidak kekal bersamanya. (Sesungguhnya mata mereka tidak buta, melainkan yang buta adalah hati yang di dalam hatinya. QS. al-Hajj: 46)
Pada kesempatan kali ini, Mbah ‘Athaillah menginginkan kita sebagai manusia yang jauh dari kebasahan spiritual agar selalu mengingat Allah sebagai sesuatu yang Maha segalanya, bahwa lagi-lagi kesadaran harus dilatih agar tetap selalu di dalam keadaan ihsan.
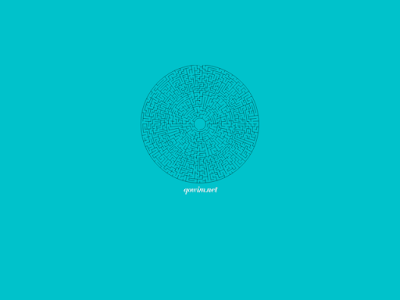 |
| qowim.net |
Cara pandang beragama kita sudah terlanjur matrealistis, bahwa sesuatu yang wujud dan dapat ditangkap oleh kelima indera kita adalah wujud yang riil, nyata, inilah yang terlanjur dipahami sebagai realitas. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera adalah yang tidak wujud, keberadaannya disangsikan, bahkan tidak dianggap ada.
Berkali-kali kita menganggap demikian. Paradigma yang matrealistis seperti inilah, yang akan menjerumuskan kita ke jurang spekulatif dalam beragama, memandang agama atas dasar untung-rugi, bahkan sampai pada tingkatan menunggangi agama demi memperoleh dunia. Ini fatal.
Saya akan memberikan penjelasan bahwa realitas tidak hanya melulu yang bisa ditangkap oleh semata-mata oleh indera. Ini persoalan filsafat sebenarnya, saya sendiri tidak mau kalau terjebak dalam pembahasan ini yang begitu njelimet.
Namun, sedikitnya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan bahwa realitas tidak melulu materi yang bisa ditangkap kelima indera kita.
Pertama, untuk melihat sebuah realitas tidak semata-mata menggunakan indera kita. Ada ruang kosong antara kita sebagai subjek dan realitas sebagai objek, dan ruang kosong itulah yang bisa disebut sebagai pemahaman (understanding), pemahaman di sini sarat dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, bahkan interpretasi kita terhadap objek yang kita lihat. Kita sama-sama melihat objek, katakanlah sebuah “gelas kosong”
Masing-masing kita akan memberikan kesan yang berbeda soal gelas kosong tersebut. Mungkin saya akan menjadikan gelas kosong itu sebagai vas bunga, yang lain menjadikannya gelas untuk minum sebagaimana fungsi awalnya, ada yang menjadikannya sebagai asbak tempat membuang putung rokok, dst.
Terlepas dari salah-benar atau tepat tidaknya pemahaman itu persoalan yang lain, tapi yang jelas adalah, bahwa kita sebagai subjek adalah independen untuk melihat objek, dan sebagai objek adalah sesuatu yang bebas untuk dimaknai sebagai apa. Inilah yang disebut sebagai relatifitas materi. Materi yang kita lihat tidak pernah berdiri sendiri, tapi penuh dengan intervensi subjek, yakni kita.
Kedua, pertanyaan yang muncul dari penjelasan pertama adalah, lalu di mana letak materi yang bisa ditentukan tanpa bantuan subjek indera manusia?. Adalah rentetan kejadian secara kronologis, bahwa sebuah kejadian C secara psikologis, kadang secara absolut ditentukan oleh kejadian sebelumnya, A dan B, meskipun ini tidak absolut, namun jika kita percaya bahwa C sebagai materi –gelas kosong dalam konteks permisalan ini– yang ditangkap oleh subjek indera, maka ketahuilah bahwa C ditentukan oleh kejadian A dan B yang terjadi sebelumnya, dengan demikian apakah kita menafikan bahkan menganggap tidak ada realitas A dan B, bahwa gelas itu dibuat dari kaca, dicetak, dan mengalami proses panjang untuk menjadi sebuah gelas (kosong).
Dengan demikian kejadian A dan B adalah realitas yang kita mengetahuinya tanpa melewati kelima indera kita.
Kedua hal di atas sangat penting untuk dipahami, bahwa materi bukanlah satu-satunya realitas, tapi sesuatu yang immateri, nonfisik bahkan meta-fisik juga bisa disebut sebagai realitas.
Saya sepakat dengan Martin Lings yang mengatakan di dalam bukunya What is Sufism? bahwa doktrin Islam yang paling bernuansa sufistik adalah keterkaitan segala entitas yang ada di semesta ini, baik secara makro kosmos maupun mikro kosmos.
Jadi Islam tidak pernah mengajarkan independensi materi apapun itu. Segala yang tampak oleh indera kita, sekaligus apa yang kita pahami dan gunakan sebagai pengetahuan adalah satu pada hakikatnya, yakni bersumber dari Maha Agung Allah.
Di dalam al-Qur’an sendiri pun menyebutkan hal yang paling parsial sekalipun, bahwa jatuhnya daun dari pohon itu tidak pernah luput dari Allah yang maha mengetahui (al-An’am: 59), semua sudah didisain sedemikian rupa agar berjalan digaris Allah, dan tidak mungkin keluar dari marka garis tersebut.
Terkait dengan aforisma Mbah ‘Athaillah di atas, adalah kritik betapa bodohnya orang yang melepaskan diri dari entitas yang Allah yang Esa, bahwa segala yang kita sebut sebagai materi dan realitas adalah sebuah fatamorgana belaka, kamuflase.
Sedangkan kita sendiri selalu mengejar hal itu, kemudian alpha dengan hakikat dari realitas tersebut; Allah. Orang bekerja demi memperoleh harta yang banyak untuk memperkaya diri, orang belajar bertujuan untuk membodohi, bahkan agar memperoleh pekerjaan yang layak dan gaji banyak, orang belajar agama untuk menyesat-kafirkan sesamanya, saking sibuknya mempersoalkan orang lain, ia sendiri lupa dengan dirinya sendiri.
Inilah yang heran di mata Mbah ‘Athaillah.
Kita sibuk mengejar tujuan yang dianggap paling penting dalam hidup ini, tapi lupa bagaimana proses memahami tujuan itu dan berproses dengan baik.
Ini tidak bermaksud mengesampingkan pekerjaan, belajar, dan sekolah, bahkan tidak memperbolehkannya, yang menjadi persoalan di sini adalah tentang pemahaman kita soal kesibukan kita sebagai manusia, bekerja dan belajar hanyalah sebagai penghubung (washilah) agar kita tidak sibuk dengan hal-hal yang buruk, tapi semua itu tidak dijadikan sebagai sandaran utama dalam hidup, sebab semua itu tidak abadi, dan kapanpun sandaran itu akan roboh, lalu kita pun ikut terjatuh.
Sedangkan sandaran yang tidak akan pernah jatuh dan abadi, tidak lain hanyalah Allah, maka seharusnya kita bersandar kepada-Nya, bukan kepada selainnya, sebab Allah tidak akan pernah roboh, dan ketika kita menyandarkan semuanya kepada Allah, maka pada saat itu juga dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah roboh, karena sandaran kita kokoh, kuat dan terpercaya, yaitu Allah.
Kenapa Allah dijadikan sandaran kita dalam segala hal?. Semata-mata karena Dia adalah dzat yang tidak pernah lepas dari diri kita, sepersekian detik pun tidak pernah. Bagaimana bisa lepas, kita hidup saja bergantung pada rahmat yang selalu diberikan-Nya, hal yang sering luput kita sadari saja, yakni detak jantung kita.
Oleh sebab itu Allah itu lebih dekat dari urat nadi seorang hamba (QS. Qaff: 16), di manapun dan kapanpun Allah selalu meliputi di setiap detik kita, dengan kesadaran seperti demikian cukup untuk dijadikan modal awal dengan mengatakan bahwa, hanya orang bodoh yang menyandarkan harapannya kepada apa yang telah diusahakannya, sedangkan usahanya itu kosong melompong tanpa isi jika tanpa diawali dengan rahmat Allah yang didapatinya.
Mata kepala kita tidak cukup untuk melihat betapa agungnya rahmat Allah di dalam diri kita, merujuk ayat yang terdapat dalam aforisma di atas, “mata mereka tidaklah buta, melainkan mata hati mereka yang buta.”
Jelas bahwa mata kepala kita sangat terbatas karena sarat akan menilai secara matrealistis saja, butuh perenungan, pemahaman sekaligus perasaan kita untuk melihat kebesaran dan kehadiran Allah yang selalu mengawasi dan memberi apapun yang kita butuhkan.
Pemahaman, perenungan dan perasaan inilah yang menurut saya adalah mata hati.

